Catatan Teater Kolosal Bajing Ketapang
Saijah dan Adinda, Kisah Romantis yang Bukan Picisan
Rabu, 08 Maret 2017 10:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
“Saijah..! Saijah....! Maafkan aku Saijah! Aku pergi ke Lampung, Saijah.”
PASASE di atas adalah kalimat yang keluar dari mulut Adinda saat pergi dari kampung Badur menuju Lampung meninggalkan kekasihnya, Saijah, yang baru pulang merantau dari Batavia. Pemeran Adinda bermain begitu menjiwai. Dengan suara parau dan isak tangis, Adinda mampu membuat sebagian penonton merasa sesak dada dan iba.
Saijah dan Adinda adalah sepasang kekasih, tokoh romantik dalam naskah pertunjukan kolosal Bajing Ketapang karya Oky Dwi Cahyo, seorang seniman muda asal Kelurahan Jetak. Pertunjukan ini digelar oleh BEM Sekolah Tinggi Kesehatan Insan Cendekia Husada (STIKes ICsada) pada malam Minggu lalu (04/03/2017) di gedung Tri Dharma Bojonegoro.
Bajing Ketapang sendiri merupakan adaptasi dari novel Max Havelaar karya Multatuli, nama pena Eduard Douwes Dekker, seorang asisten residen di Lebak, Rangkas Bitung, Banten pada zaman kolonial Belanda. Novel ini telah berusia lebih dari 150 tahun, namun hingga kini masih dibaca dan diperbincangkan.
Melalui Bajing Kepatang ini, penonton seakan disodori versi mudah dari novel setebal 400 halaman yang terkesan sulit dibaca ini. Sebab novel ini ditulis dengan cara yang tidak konvensional serta tidak begitu beraturan. Ada beberapa narator yang saling bergantian dan bertabrakan pada bagian-bagian dalam novel. Otomatis itu kerap membuat pembaca bingung. Dalam pembuka novel ini sendiri disebutkan bahwa pengarang tidak suka berindah-indah dalam menulis. Maka, pementasan Bajing Ketapang bisa disebut sebagai salah satu cara memudahkan orang untuk membaca.
Pertunjukan Bajing Ketapang berdurasi lebih dari 2 jam. Cukup panjang untuk penonton di Bojonegoro yang biasa menikmati tontonan tak lebih dari 1 jam, kecuali konser band tentu saja. Meski demikian, gedung Tri Dharma malam itu dipenuhi lebih dari 500 penonton meski harus membayar tiket.
Kembali tentang Saijah dan Adinda. Dua tokoh ini dikisahkan menjalin hubungan asmara. Mereka bermain bersama sejak kecil dan lambat laun berkomitmen untuk hidup bersama, kawin. Namun Saijah ingin pamit dahulu mengadu nasib ke Batavia. Saijah berjanji akan menemui dan menikahi Adinda saat kembali kelak. Janji mereka diucapkan di bawah pohon ketapang. Di bawah pohon ketapang inilah nantinya mereka akan bertemu kembali.
Bukan Picisan
Naskah Bajing Ketapang, pun Max Havelaar, tentu bukan kisah romantik picisan yang mengutamakan pertemuan dua insan lawan jenis lalu pacaran lalu menikah dan seterusnya. Bukan sekadar itu tentu saja, kalau melihat fakta bahwa novel ini ternyata mampu menghentikan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Berkat novel Max Havelaar ini, Pemerintah Belanda menghentikan kebijakan itu karena dinilai telah keluar jalur dari yang semestinya sebab banyak terjadi praktik penindasan dan korupsi, berganti politik etis. Karena diberlakukannya politik etis inilah, akhirnya pribumi (meski tak semuanya), bisa mengenyam pendidikan modern.
Praktik penindasan, kekejaman dan korupsi sudah mengakar kuat, bahkan pada para pejabat atau priyayi pribumi, sehingga menjadikan rakyat kecil sebagai korban. Saijah dan Adinda juga menjadi korban. Mereka tidak bisa bertemu lantaran dirampas hak kebebasan dan hartanya oleh penguasa pada saat itu. Kisah mereka menjadi tragik yang menggugah jiwa. Saijah yang menunggu di bawah pohon ketapang setibanya dari Batavia tak mendapati kekasihnya datang. Bajing-bajing menari menyaksikan pembuktian janji dan penantian Saijah.
Di antara itu, muncul Max Havelaar, asisten residen yang dikenal lurus. Dia tidak setuju dengan perilaku korup dan kejam bupati saat itu. Dia protes, namun kondisi tidak mendukung. Penyelewengan kekuasaan telah menggurita. Cukup berat untuk dilawan seorang diri yang seperti Max Havelaar. Protesnya tidak ditanggapi dan malah mendapat respons dengan suap. Namun Max yang malang menolak dan memilih pulang ke negerinya, Belanda.
Multatuli
Dalam pementasan ini, Multatuli hadir di luar cerita. Dia sebanyak 4 kali muncul untuk memberikan penjelasan kepada penonton, tentang tokoh Max dan ceritanya.
Di awal, Multatuli muncul berdiri menjinjing koper dan mengatakan tentang jati dirinya sebagai penulis Max Havelaar. “Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya anggap Anda semua tidak hanya sebagai penonton, namun juga sebagai pembaca. Ya, pembaca. Bahwa sayalah Multatuli, yang telah menuliskan hal-hal yang mengusik hati saya, melihat banyak kecurangan, penindasan, dan banyaknya pemerasan yang dilakukan para pejabat-pejabat Belanda dan juga pejabat-pejabat di daerah itu sendiri. Dan semua itu sungguh menyedihkan bagi saya.”
Di tengah, saat adegan Slotering, asisten residen sebelum Max Havelaar, mati setelah menghadiri sebuah perjamuan makan malam, Multatuli juga muncul, masih dengan kopornya. Dia muncul dan menerangkan bahwa Slotering mati diracun.
Di akhir, Multatuli juga muncul. Dia menegaskan bahwa cerita Max Havelaar serta Saijah dan Adinda adalah kisah mengharukan sekaligus menjemukan. “Betapa mengharukan! Sudah kukatakan bahwa kisah ini akan menjemukan. Mereka telah pergi meninggalkan Badur, sebab rumah-rumah mereka sudah habis dibakar karena selalu terlambat membayar pajak. Dan di Lampung ada peristiwa tragis dimana di sana pemberontak akan ditumpas habis.”

Kisah ini disebut-sebut sebagai based on true story sekaligus biografis bagi pengarangnya, Multatuli alias Eduard Douwes Dekker. Maka dengan demikian, Max Havelaar sendiri sebenarnya adalah representasi dari pengaranganya (Multatuli). Kisah Max Havelaar ditulis selang beberapa tahun setelah Eduard Douwes Dekker pulang dari Hindia, di sebuah losmen di Belanda. Buku ini diterbitkan di berbagai negara.
Semangat Literasi
Pertunjukan ini menjadi semacam refleksi bagi para mahasiswa STIKes ICsada Bojonegoro terhadap budaya literasi. Ini nampak betul lewat adegan prolog di pertunjukan ini, ada sekelompok muda-mudi yang memegang buku dan pusing dengan apa yang tengah mereka baca. Mereka tak tahan membaca dan malah asyik dengan gadget serta beragam media sosial seperti whatsapp, facebook, smule, dan lain sebagainya.
Buku bagi para anak-anak muda yang alay itu adalah sesuatu yang membosankan dan bikin pusing.
Prolog itu mengantarkan penonton untuk memahami bahwa di tengah beragam produk modernisme yang menawarkan kepraktisan dan gaya hidup yang hedon, buku masih ada dan dibaca. Buku Max Havelaar karya Multatuli alias Eduard Douwes Dekker salah satunya, yang saat ini berusia lebih dari 150 tahun. (ver/moha)

Foto - foto: dokumentasi BEM STIKes ICsada
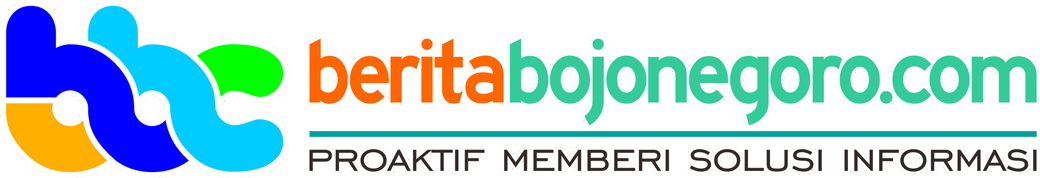


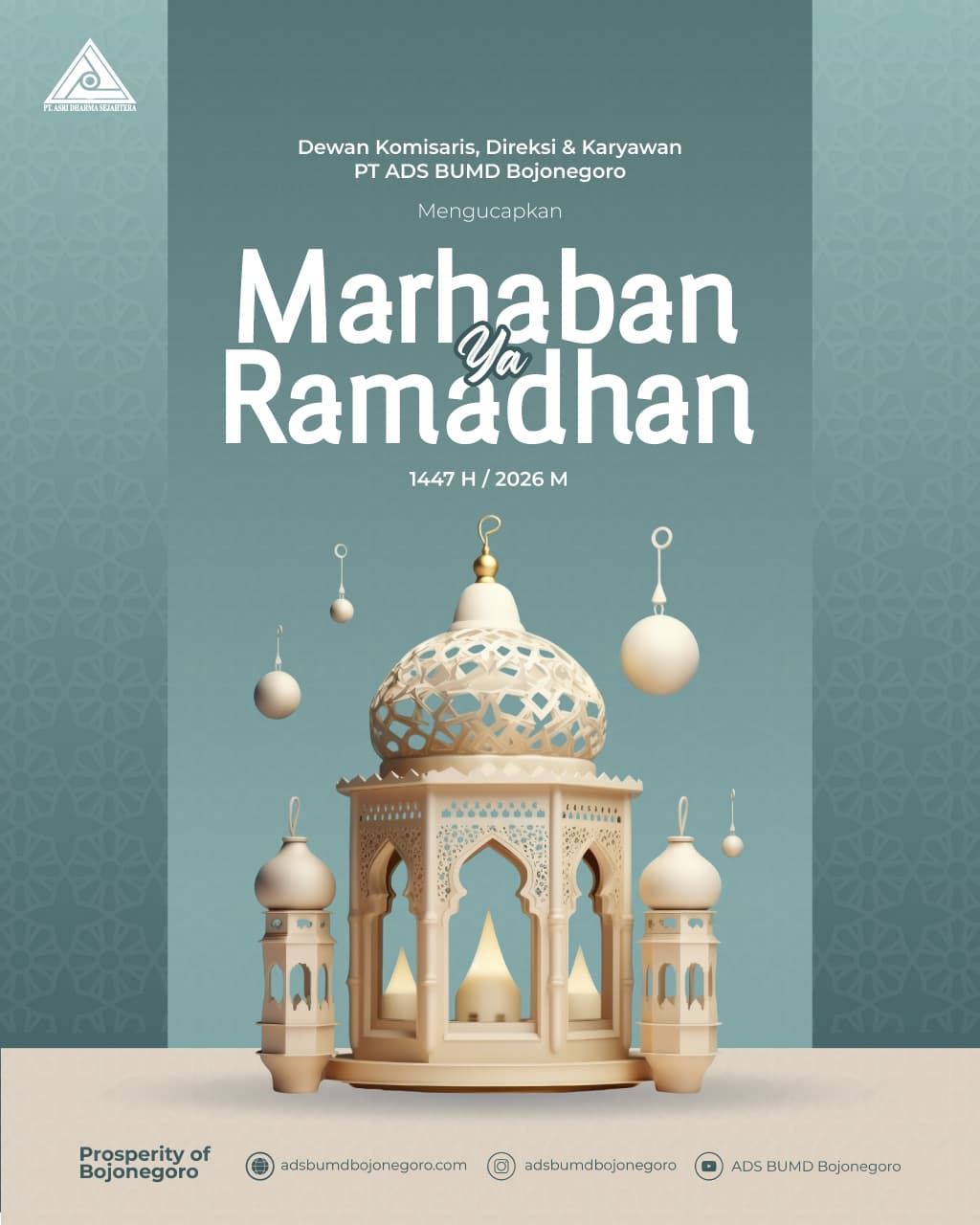








.sm.jpg)




















.md.jpg)






