Mereka yang Bergerak dari Pinggir
Kamis, 20 Agustus 2015 08:00 WIBOleh Erliza Achmad Akbar *)
*Oleh Erliza Achmad Akbar
Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merdeka
Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih di kandung badan
Kita tetap setia tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap setia
Membela negara kita
Mungkin pembaca sudah akrab dengan lagu yang rutin dinyanyikan setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Lagu yang diciptakan oleh HS Muthohar (Habib Husein bin Salim Al-Muthohar), paman Habib Umar Muthohar asal Semarang tentu rutin menghiasi setiap kegiatan perayaan Agustusan di sekolah dan instansi pemerintahan umumnya. Baiklah, mari kita kumandangkan lagi. Setuju?
Lupakan sejenak kelesuan ekonomi negara kita akhir-akhir ini, lupakan sejenak kesedihan akibat konflik keagamaan yang pecah bulan silam, lupakan dulu nilai tukar dolar yang melambung. Marilah kita sambut bulan yang sakral dengan gegap - gempita dan penuh sukacita ini dengan banyak cara tentu saja.
Saya percaya jika di dalam setiap anak bangsa yang lahir di sudut Nusantara tertanam jiwa nasionalisme. Jiwa yang selalu bergetar dan tertunduk haru saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Terlepas dari sepanjang 70 tahun negara ini yang tegak dengan jalan berdarah - darah dan penuh pengorbanan dari pahlawan ini belum sesuai dengan apa yang dicitakan sejak dulu, ini lain soal. Selebrasi tetaplah selebrasi. Bukankah kehidupan terkadang bukan bergerak dari waktu ke waktu, melainkan dari suasana ke suasana?
Dengan cara apa kemerdekaan itu dinyatakan?.Dengan cara apa kemerdekaan itu diisi?.Dan untuk apa kemerdekaan itu dinyatakan?Tentu jadi pertanyaan lagi setelahnya.
Bahwa begitu banyak orang yang menganggap Indonesia adalah panggilan jiwa dan dengan demikian dianggap juga sebagai tugas personal masing - masing yang mutlak dimiliki jika ingin dianggap sebagai civil society yang baik, maka setiap perayaan Agustusan mungkin adalah sebuah panggung kecil tempat dimana orang punya kesadaran yang sama.
Di kampung saya, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, gaung kemerdekaan itu masih tetap terjaga dari dahulu sampai detik ini. Lazimnya perayaan tujuh belasan di tempat lain, jauh hari beberapa bulan sebelumnya, para pemuda yang cangkrukan sudah mengobrol ringan dalam sebuah percakapan sederhana. Apa saja lomba kemerdekaan tahun ini? Apakah karnaval nanti memakai kostum yang berbeda dari tahun lalu atau masih sama memakai kostum bencong dengan selendang warna-warni dengan susu buatan dari balon yang diisi air? Apa yang disiapkan agar berbeda dari pawai peserta lain? Jadi perhatian publik. Publik sepanjang jalan itu tentunya.
Lalu di warung mungkin sebagian sudah bicara juga soal bagaimana mekanisme penggalangan dana untuk lomba nanti, cara menggertak lurah agar keluar dana lebih banyak ,menggalang kolektivitas orang kaya kampung agar sudi meminjamkan mobil boks untuk pawai atau membiayai sound sistem yang mengggelegar sepanjang jalan, atau sekedar sumbangan jajanan ringan berupa beberapa besek telo godok dan kacang godok. Semua bergerak. Semua ingin punya peran.
Bahkan saking pentingnya, kontroversi seputar rute yang diambil saat gerak jalan saja mampu memicu keributan serius di kalangan antar desa. Bayangkan, betapa acara tujuh belas Agustusan di sini adalah panggung buat mereka orang biasa-biasa saja dalam peran keseharian yang ingin menunjukkan jati dirinya.
Jadi, saat ada pengumuman rute gerak jalan Tinggang-Bojonegoro sejauh 45 kilometer dialihkan ke jalur selatan yang dianggap tidak akan mengganggu lalu lintas poros utama Cepu-Bojonegoro, protes pun bermunculan. Menurut mereka, di hari itu satu-satunya kesempatan untuk bisa menunjukkan ke orangtua, kerabat dan teman dekat yang menonton dari pinggir jalan sambil bertepuk tangan riuh.
Aris,seorang pemuda lugu yang dalam keseharian jadi pelayan warung kopi di pertigaan telon bisa mendadak tenar saat memakai jas dan kacamata hitam. Betapa kembang - kempis hidungnya saat pujian meluncur dari dandanannya itu.
Sigit, seorang kuli panggul pasar, bisa jadi pak lurah yang tertunduk lesu dengan dandanan khas seorang pejabat saat memainkan lakon tersangka korupsi dan diarak warga. Tapi tentu timbul kebanggaan di dirinya karena di hari itu dia bisa melampaui ekspektasi orang terhadap apa yang tidak pernah dicapai sepanjang hidupnya. Menjadi lurah. Meski hanya acara karnaval yang apus-apusan.
Semua butuh panggung di perayaan Agustusan ini, semua ingin tampil tidak biasa biasa saja. Semua ingin dapat tepuk tangan atau sekedar decak kekaguman. Pernah dengan ungkapan ini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan-pekerjaan biasa oleh Sanento Yuliman. Sanento Yuliman, orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor seni rupa, menjelaskan hal itu dengan satu kalimat dalam esainya yang menarik, Di Bawah Naungan Para Pahlawan. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan-pekerjaan biasa,” tulisnya.
Parafrase Sanento itu menarik untuk diletakkan dalam kerangka imajinasi produktifnya Paul Ricoeur yang memungkinkan lahirnya gambaran kebangsaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ada sebuah horison di masa depan yang di dalamnya diimajinasikan sebagai yang berbeda, liyan, dari sebelum-sebelumnya, yang bagi Ricoeur akan mewedarkan apa yang disebut sebagai horison pengharapan (horizon of expectation). Ini berhadapan dengan jenis imajinasi reproduktif (Oleh Ricoeur disebut reproductive imagination), sejenis imajinasi yang minimalis kadarnya, karena ia muncul sebagai peng-iya-an dari masa silam dan sesuatu yang –dalam bentuknya yang ekstrim– biasa memunculkan sikap getol dan keukeuh melap-lap warisan masa silam. (Zen.RS dalam esainya berjudul Kepahlawanan di Era Post-Nasionalisme).
Imajinasi produktif ini membuka diri pada pentingnya sikap, tindakan atau pekerjaan biasa yang mungkin tidak terlampau gagah dan heroik, yang dilakukan bukan oleh pribadi yang siap menyerahkan raga dan nyawa bagi keutuhan NKRI, tapi hanya seseorang yang melakukan pekerjaan biasa atau merealisasikan ide-ide yang sederhana – pendeknya sesuatu yang tak bersifat epik yang berdaya auratik.
Merekalah yang saya sebut sebagai pegiat acara kemerdekaan sesungguhnya. Para pemuda yang dianggap menganggur dan luntrang lantrung gak jelas justru tampil terdepan dalam menyusun rapat kecil di warung kopi. Memviralkan pesan untuk mengisi perayaan semeriah meriahnya. Sebesar besarnya.
Merekalah yang terus bergerak dari pinggir. Dari sudut - sudut kios pasar memungut receh demi receh sumbangan dari pedagang agar terkumpul iuran. Mereka yang berletih - letih menyusun susunan panitia dan pembagian kerja, mendirikan panggung, menghias becak untuk pawai, mungkin juga pedagang yang rela kulakan bendera dan merelakan dagangannya didiskon untuk sekadar memanteskan gapura dengan bendera dan umbul-umbul. Mereka yang menghias gapura aneka warna, memupurinya dengan gamping. Mereka yang berleleran keringat berlatih gerak jalan dengan peluit nyaring. Mereka yang membuntuti peserta lomba gerak jalan dan bertugas menyediakan konsumsi dari sepeda motor mereka. Sebuah kesadaran kolektif.
Merekalah yang tidak merutuki gelap, tapi mereka yang lebih memilih menyalakan lilin, betapa pun sayu dan kecilnya nyala lilin itu. Kita butuh mereka itu justru karena persoalan yang dihadapi terlampau banyak, bertumpuk, beragam bidang dan aspek. Kita tak bisa lagi hanya berharap pada lurah, perangkat desa, atau seorang ulama – pendeknya. Orang-orang penting atau nama-nama besar sebab mereka terkadang lebih fokus ke bidang koordinasi. Mereka sudah punya panggung sendiri yang wangi, yang agung, keramat dan tak bakalan diusik karena dalam keseharian sudah dianggap punya nilai peran lebih dari kebanyakan liyan.
Setidaknya jika kita tidak pernah bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik, dalam perayaan tujuh belas Agustusan ini marilah berikan kesempatan seluasnya bagi mereka yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap tidak punya peran menonjol di lingkungan jadi sesuatu yang bukan mereka dalam keseharian mereka. Berikan mereka panggung agar jadi lebih berarti. Jadikan mereka lebih berarti.
Dirgahayu Indonesiaku. Salam
*Penulis adalah pegiat Komunitas Langit Tobo
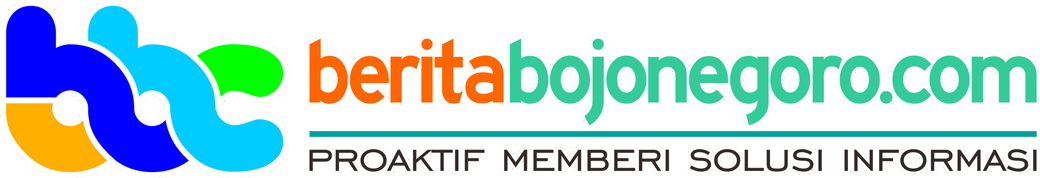































.md.jpg)






