Jejak Para Pejuang Kemerdekaan
Jumat, 21 Agustus 2015 07:00 WIBOleh Liya Yuliana *)
*Oleh Liya Yuliana
Sejarah bukanlah sumber hukum, namun dari sejarah manusia dapat mengambil ibrah dan berbenah. Sejarah tergantung pada siapa yang menuliskan dan kapan ia dituliskannya. Latar belakang biografi penulis juga sangat berpengaruh. Jika kita tengok sisi lain dari sejarah yang tengah berkembang mengenai para sosok pahlawan, didapatkan sosok Pangeran Diponegoro. Menurut Babad Diponegoro yang beliau tulis di Penjara Menado, sejak muda beliau telah mengabdi untuk agama, mengikuti jejak moyangnya yang sangat taat beragama. Pemuda yang bernama Bendoro Raden Mas Ontowiryo sewaktu kecil ini mendapat gemblengan langsung dari neneknya (permaisuri dari HB I Ratu Ageng Tegalrejo) sehingga minat belajar Islamnya tinggi. Di tempat ini pula selain memperdalam pengetahuannya tentang Islam, beliau juga secara tekun melaksanakan ketentuan-ketentuan syariah Islam.
Dalam memimpin Perang Jawa Pangeran Diponegoro senantiasa tersuasana oleh syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari surat Diponegoro yang ditujukan kepada penduduk Kedu, yang ditulis dalam bahasa Jawa, antara lain berbunyi: “Surat ini datangnya dari saya, Kanjeng Gusti Pangeran Diponegoro bersama dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta Adiningrat, kepada sekalian sahabat di Kedu, menyatakan bahwa sekarang kami sudah minta tanah Kedu. Hal ini harus diketahui oleh semua orang baik laki-laki maupun perempun, besar atau kecil, tidak usah kami sebutkan satu demi satu. Adapun orang yang kami suruh bernama Kasan Basari. Jikalau sudah menurut surat undangan kami ini, segeralah sediakan senjata, rebutlah negeri dan betulkan agama Rasul. Jikalau ada yang berani tidak mau percaya akan bunyi surat saya ini, maka dia akan kami penggal lehernya.”
Berada di samping Pangeran Diponegoro seorang penasihat dan ulama terkenal dari daerah Mojo Solo yakni Kiai Mojo. Tatkala perang dicetuskan sang Kiai bersama anaknya, Kiai GazaIi, dan para santrinya bergabung dengan pasukan Diponegoro. Langkah yang ditempuh oleh Diponegoro adalah mengeluarkan seruan kepada seluruh rakyat Mataram untuk sama-sama berjuang menentang penguasa kolonial Belanda dan para tiran yang senantiasa menindas rakyat. Seruan itu berbunyi: “Saudara-saudara di tanah dataran. Apabila saudara-saudara mencintai saya, datanglah dan bersama-sama saya dan paman saya ke Selarong. Siapa saja yang mencintai saya, datanglah segera dan bersiap-siap untuk bertempur.”
W.F. Wertheim dalam tulisannya menyatakan bahwa faktor baru muncul pada abad ke-19 saat rakyat Indonesia banyak yang masuk Islam. Hal ini memperkuat posisi yang mengandalkan dukungan kuat dari rakyat. Para penguasa kolonial Belanda terus-menerus berkonfrontasi dengan sultan-sultan Indonesia. Hal ini mendorong mereka untuk mempersatukan diri dengan para kiai untuk memperjuangkan Islam.
Selain Pangeran Diponegoro, kita dapati Tuanku Imam Bonjol, pahlawan yang begitu harum namanya. Perang Padri menjadi saksi perjuangannya. Perang yang terjadi di kawasan Kerajaan Pagaruyung antara tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri muncul sebagai sarana Kaum Padri (Kaum Ulama) dalam menentang perbuatan-perbuatan maksiat seperti kesyirikan (mendatangi kuburan-kuburan keramat), perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (opium), minuman keras, tembakau dan aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan (yang menyalahi aturan Islam) dan umumnya pelonggaran pelaksanaan kewajiban ibadah agama Islam.
Perang Padri merupakan peperangan yang meninggalkan kenangan heroik sekaligus usaha penegakkan syariah Islam di Ranah Minang. Pada awalnya, timbulnya peperangan ini didasari oleh adanya keinginan para ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariah Islam sesuai dengan Manhaj Salaf. Pemimpin para ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku Pasaman (Tuanku Lintau) untuk mengajak Raja Pagaruyung, Sultan Muning Alamsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada kata sepakat antara Kaum Padri dan Kaum Adat. Muncullah gejolak diantara mereka. Kaum adat meminta bantuan Belanda dengan kompensasi penyerahan beberapa wilayah darek (pedalaman Minangkabau). Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Melalui Residen di Padang Belanda mengajak pemimpin Kaum Padri Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat “Perjanjian Masang” pada tanggal 15 November 1825. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul Kaum Adat. Muncullah suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus “Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Adat berdasarkan Agama, Agama berdasarkan Kitabullah [al-Quran])”.
Dari perjanjian inilah, perang berubah menjadi perang antara Kaum Adat dan Kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda. Pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Semangat para pahlawan melawan kaum penjajah didasari oleh semangat melaksanakan seruan Allah (kewajiban berjihad saat diperangi musuh). Seruan untuk membebaskan diri dari kezaliman dan penghambaan sesama manusia karena penjajahan haram terjadi di bumi pertiwi. Allahu A’lam.
*Penulis adalah guru SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro.
Sumber foto ilustrasi net
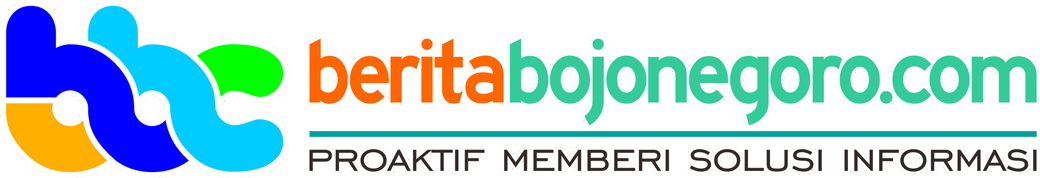























.sm.jpg)







.md.jpg)






