Buku Arus Bawah Karya Emha Ainun Najib
Cerita Punokawan dalam Masyarakat Kita
Minggu, 26 Maret 2017 11:00 WIBOleh Muliyanto
Oleh Muliyanto
DALAM buku novel semi esai berjudul Arus Bawah ini, Emha Ainun Najib alias Cak Nun menggagas berbagai fenomena sosial masyarakat. Cak Nun memakai wayang, dalam hal ini punokawan, sebagai alat untuk menjelaskan fenomena sosial.
Melalui analogi pewayangan, barangkali Cak Nun menggambarkan bahwa rakyat adalah para punakawan. Buku ini sendiri merupakan kumpulan esai-esai yang muncul di Harian Berita Buana dan terbit pada 28 Januari sampai 31 Maret 1991. Pada tahun 1994, kumpulan esai itu berubah menjadi novel-esai pada 1994. Pada zaman itu sendiri, orang-orang tidak bebas dalam menyampaikan opininya. Apalagi jika pendapat mereka berkaitan dengan politik dan kekuasaan yang saat itu mencengkeram rakyat.
Walaupun telah menjadi gagasan yang lahir pada masa orde baru duabelas tahun, esensi yang disuguhkan oleh Cak Nun tetap relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Barangkali, semenjak runtuhnya rezim orde baru, reformasi memang belum memberikan efek yang signifkan. Tulisan-tulisan dalam buku ini sendiri merupakan esai yang dinovelkan. Jadi, seolah-olah kita membaca novel-esai. Dalam setiap tulisannya, Cak Nun menyampaikan gagasan yang diperagakan oleh para punakawan. Bak membaca cerpen bersambung, tulisan ini seolah-olah adalah esai-esai yang “diselundupkan” dalam cerita pendek agar tidak ketahuan oleh orde baru.
Cak Nun sendiri dalam buku “Arus Bawah” menjadikan para punakawan sebagai tokoh sentral. Pada bab pertama, kita akan disuguhkan cerita tentang hilangnya Semar. Namun, satu-satunya yang mengkhawatirkan hilangnya Semar adalah Gareng, si sulung dari Punakawan. Petruk tampak tenang-tenang saja dan tidak mengindahkan kecemasan abangnya. Sementara itu, Bagong terkesan menjadi yang paling kurang ajar dan tidak tahu diri.
Kita tahu sendiri bahwa Punakawan adalah tokoh pewayangan yang hanya menjadi figuran. Mereka tampil sebagai sosok-sosok humoris yang menghibur. Ya, para punakawan itu hanya berlaga di atas panggung untuk menghibur. Namun, di esai-esai yang ditulis oleh Cak Nun, ia menunjukkan bahwa Punakawan adalah tokoh-tokoh sentral. Dalam buku ini sendiri, Cak Nun sering mengaitkan beberapa cerita-cerita wayang seperti terbunuhnya Arjuna tatkala bertarung dengan Bambang Ekalaya. Pada pertempuran itu, para punakawan tiba-tiba meyakini bahwa mereka memiliki peran penting dalam kisah itu. Mereka tidak hanya menghibur dengan beragam lelucon, mereka adalah entitas dari segala sistem yang sedang berjalan.
Para punakawan ini sendiri menggugat. Dalam buku ini, Cak Nun menyuguhkan adegan di mana para punakawan mendadak tidak nyaman dengan dirinya yang selalu patauh terhadap dalam. Mereka hendak menggugat dan ingin mengambil alih. Terutama ketika cerita-cerita yang disampaikan oleh para dalang selalu dan selalu menyiratkan penderitaan para rakyat. Seolah-seolah penindasan itu telah diskenariokan.
Salah satu yang menarik di sini adalah bagaimana Bagong hadir dalam tulisan-tulisan Cak Nun sebagai sosok yang mendekontruksi nilai-nilai pemahaman yang ada. Jika kita mengenal Bagong sebagai sosok punakawan paling lucu. Maka di sini kita akan berpikir tentang Bagong berulang kali. Dalam pewayangan sendiri, Bagong digambarkan begitu jelek dengan bibir ndower yang sangat besar dan tubuh gendut dengan bokong yang yang besar pula.
Terlepas dari perawakannya itu, Bagong seolah-olah menjadi sebuah antitesis dari segala fenomena yang ada. Ia telah mendobrak dan barangkali menjadi cerminan dari arus bawah itu sendiri. Bagamana ia menolak memanggil Semar dengan sebutan Bapak dan juga menolak memanggil saudara-saudaranya dengan sebutan yang lebih tua. Dalam buku ini, Bagong bukan lagi entitas humoris yang selalu menghibur. Ia adalah esensi dari sebuah kebijakan walaupun disampaikan dengan kebanalan.
Dalam buku ini, Bagong disebut-sebut sebagai perwakilan bagian dari kiai Semar sendiri: bagian yang memberontak terhadap keniscayaan tugas-tugasnya sendiri. Muncul saat orde baru, esai-esai ini sesungguhnya adalah kritik terhadap kekuasaan yang membelenggu dan menindas. Digambarkan dengan peristiwa-peristiwa pewayangan, hilangnya Semar adalah hilangnya jiwa dalam rakyat itu sendiri.
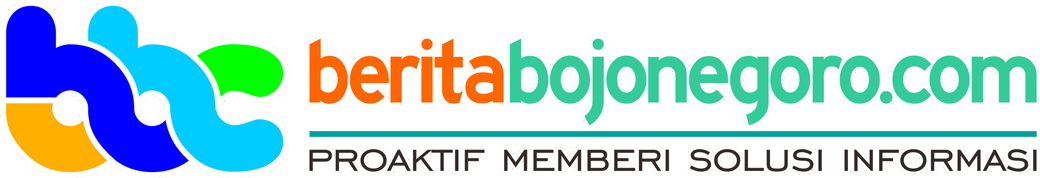
























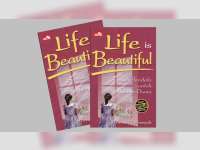






.md.jpg)






