Pesantren dan Kebudayaan Tulis (sebuah otokritik)
Sabtu, 03 Oktober 2015 22:00 WIBOleh Shuudin Aziz
Oleh Shuudin Aziz
PENGALAMAN merupakan guru terbaik, demikianlah adigium yang sering kita dengar. Namun tidak sedikit dari kita yang kurang peduli dengan pengalaman tersebut, sehingga memilih membiarkannya lewat begitu saja, tanpa ada upaya untuk mendokumentasikan ke dalam sebuah tulisan.
Manusia adalah bagian dari sebuah kisah yang telah dirancang dengan cermat oleh Penulis yang Maha Agung. Setiap kejadian demi kejadian, pengalaman demi pengalaman di seluruh tataran eksistensi adalah berkelindan seperti jejaring laba-laba. Satu getaran peristiwa di satu ujung jejaring akan dirasakan dan mempengaruhi seluruh lintasan jejaring hingga ke delapan ujung jejaring itu — seperti “butterfly effect” di mana kepak sayap kupu-kupu di ujung timur dunia bisa menimbulkan badai di ujung barat dunia.
Ada banyak peristiwa atau pengalaman yang kita anggap besar/ berharga; peristiwa yang laksana angin badai datang menerpa rumah kedirian kita, membuka jendela-jendela persepsi kita, mengguncang arsitektur kesadaran kita, dan mengubah diri kita, entah itu untuk sementara atau untuk selamanya. Lalu kita berusaha merenungkan dampak peristiwa itu. Bagi diri kita sendiri, atau barangkali, bagi cara pandang kita terhadap keberadaan diri kita sebagai manusia. Namun peristiwa “besar” itu tak selalu berupa pengalaman/ kejadian historis yang mengguncang tatanan sosial atau kemanusiaan — peristiwa besar itu boleh jadi sebentuk momen pencerahan, seperti lintasan cahaya kilat di kegelapan pekat yang membuat kita memandang situasi sekitar kita yang, walau mungkin hanya sesaat, membuat kita menyadari akan adanya sesuatu yang lain.
Barangkali dalam perjalanan hidup kita, ada banyak momen-momen pencerahan atau pengalaman-pengalaman semacam itu. Namun, sayangnya, kita terlampau sibuk oleh hiruk-pikuk dunia, oleh pikiran yang seperti tiada kenal lelah menjelajah di benak kita sehingga kita lalai akan pentingnya mendokumentasikan semua/ sebagian dari pengalaman tadi ke dalam sebuah tulisan. Karena itu, beberapa orang yang peduli pada kehidupan kontemplatif merasa harus menarik diri. Setidaknya untuk sementara, untuk menangkap momen-momen pencerahan itu yang kemudian menuliskannya.
Di pesantren, jika para santri faham dan sadar akan urgensi membaca kemudian menuliskan apa yang telah ia baca ke dalam sebuah catatan atau karya tulis, maka pasantren akan kembali meraih makna hakikinya sebagai sebuah instansi yang darinyalah lahir seorang penulis-penulis handal dan produktif. Kita ambil contoh; dalam rangka menghindari ”kalap teks”(jahl ‘aninnushus) di pesantren, kitab kuning adalah faktor penting yang menjadi karakteristik pesantren. Selain sebagai pedoman bagi tata cara keberagamaan, kitab kuning juga difungsikan oleh kalangan pesantren sebagai referensi (marji’) nilai universal dalam menyikapi segala tantangan kehidupan.
Segi dinamis yang diperlihatkan kitab kuning adalah transfer pembentukan tradisi keilmuan yang didukung penguasaan ilmu-ilmu instrumental, termasuk ilmu-ilmu humanistik (adab). Tanpa kitab kuning, dalam pengertian yang lebih kompleks, tradisi intelektual sulit bisa keluar dari kemelut ekstremitas.
Seringkali muncul dalam benak, jika apa yang telah ditimba santri dari setiap pengajian kitab kuning tersebut mampu dirangkum oleh santri kemudian di tuangkan dalam sebuah tulisan semacam reportase kajian atau resensi kitab, maka tidak menutup kemungkinan akan hadir tafsir-tafsir al-Quran dari tangan para santri.
Apa yang menjadi kecemasan saya di atas muncul ketika saya membaca sebuah sejarah disusunnya buku ushul fikih pertama (ar-Risalah-sekitar abad 15) berawal dari penulisan surat asy-Syafii beserta muridnya kepada salah seorang raja ketika itu. Selain itu murid al-Ghazali (wf:505 H) yang gemar menulis kajiannya bersama sang guru juga berhasil membuahkan buku yang diberi judul ‘Ayyuha al-Walad’ yang sampai saat ini ada di tangan para santri.
Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa harus pesantren? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menawarkan jawaban sekaligus mengingatkan ulang, bahwa sejarah membuktikan pesantrenlah sebuah institusi yang telah berperan sebagai agen ortodoksi Islam yang paling penting. Ini berarti bahwa pesantren lebih banyak memperhatikan bagaimana menjaga ajaran Islam dan tarikan akulturatif berbagai unsur sistem kepercayaan lokal atau asing. Soal kesinambungan menjadi sangat penting. Akibatnya, di samping menjadi ”makelar kebudayaan” (cultural broker), pesantren juga berfungsi sebagai filter dari unsur-unsur luar yang dominan.
Secara historis, keberadaan pesantren hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Alasannya sangat sederhana. Islam, sebagai agama dakwah, disebarkan secara efektif melalui proses transformasi ilmu dari ulama ke masyarakat, dan proses ini di Indonesia berlangsung melalui pesantren. Secara etimologi, pesantren tidak sepenuhnya merujuk pada kata dalam bahasa Arab. Sebutan untuk pelajar yang mencari ilmu bukan murid seperti dalam tradisi sufi, thalib atau tilmidh seperti dalam bahasa Arab, tapi menggunakan istilah ‘santri’ yang berasal dari bahasa Sanskerta. San berarti orang baik, dan tra berarti suka menolong. Sedangkan lembaga tempat belajar itu pun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau “pesantren”.
Jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum sistem pendidikannya mapan, pesantren dan alumni-alumninya telah banyak berperan—baik di Nusantara maupun kancah dunia. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Syekh Yusuf al-Makassari (Makassar), Abdussamad al-Falimbani(Palembang), Khatib Minangkabawi (Minangkabau), Nawawi al-Bantani (Banten), dan Muhammad Arsyad al-Banjari (Kalimantan). Sosok-sosok alumni pesantren dan Timur-Tengah ini telah melahirkan karya-karya besar di bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Citra intelektual dan ekspansi karya sosok-sosok ini bukan hanya sebatas taraf domestik nusantara, tapi juga sampai diakui di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Tajamnya pena (baca;tulisan) para penulis jebolan pesantren tersebut tentunya tidak datang begitu saja seandainya mereka miskin bacaan dan tumpul daya analisis. Walaupun teknologi percetakan saat itu masih terbilang sederhana, namun harus diakui pula bahwa sistem pendidikan bahasa di zaman Belanda cukup mapan. Sebagai gambaran, tak jarang ketika itu seorang santri yang mengeyam pendidikan di luar negeri hampir bisa dipastikan ia fasih berbahasa dengan bahasa negara tersebut dan terbiasa dengan tulisan-tulisan dengan bahasa asing. Hal ini memungkinkan ia dapat secara langsung mengakses ilmu dari buku-buku kelas dunia yang ditulis dalam bahasa aslinya tanpa harus diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Sampai di sini kita dapat menarik pelajaran bahwa idealisme, nasionalisme serta kreativitas para fouding father kita secara efektif terbentuk dari budaya literer atau budaya baca – tulis, serta penguasaan bahasa asing sebagai kunci pembuka berbagai literatur pergerakan politik dunia.
Imam ‘Ali Karramallahu Wajhah pernah memberikan anjuran kepada para sahabat: “ikatlah ilmu dengan tulisan”. Jika kata Imam ‘Ali ini dipegang kuat oleh santri dalam setiap moment/ event ngaji di pesantren, niscaya karya tulis dari pesantren akan mengalir deras.
Tibanya era reformasi bagi negeri yang budaya literernya sudah terlanjur mandek, akhirnya membuat pesantren gelagapan. Televisi yang mendangkalkan kreativitas lebih dicintai ketimbang buku yang menajamkan daya analisis. Mereka lalai bahwa ada lebih banyak harta yang terkandung di dalam buku, ketimbang seluruh jarahan bajak laut yang disimpan di pulau harta karun Walt Disney. Untuk menyikapi kondisi semacam ini, dipandang sangat perlu menghidupkan semangat membaca dan menulis di pesantren.
Penulis adalah pengajar di Pondok Pesantren al-Rosyid Bojonegoro dan Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PC NU Bojonegoro.
Sumber artikel www.atasangin.com
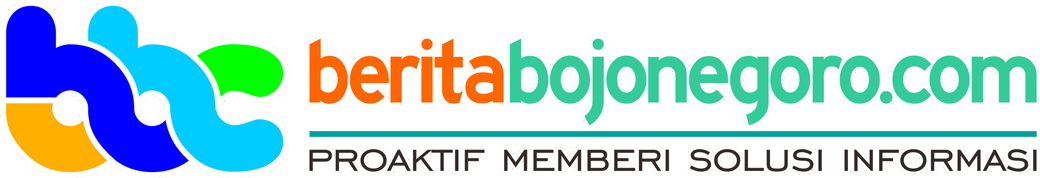























.sm.jpg)







.md.jpg)






