Buah Demokrasi dari Rukun Kematian
Sabtu, 23 September 2017 09:00 WIBOleh Drs H Suyoto MSi
Oleh Drs H Suyoto MSi
INDONESIA mendapatkan berkah demokrasi sejak reformasi. Bahkan, sejauh demokrasi itu diartikan sebagai ruang publik sebagaimana gambaran Jurgen Habermas, maka di desa telah lebih dulu ada demokrasi, jauh sebelum era reformasi. Bedanya, setelah reformasi ruang publik itu diperluas sehingga politik, ekonomi dan ruang-ruang publik itu diyakini betul-betul menjadi milik rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan masih tingginya angka kemiskinan, maraknya praktik korupsi dan hukum yang belum sepenuhnya efektif untuk keperluan pembangunan serta demokrasi yang acap kali dibajak oleh elit telah menyebabkan demokrasi belum efektif.

Demokrasi menjadi belum efektif, salah satunya, karena demokrasinya hanya bersifat prosedural sehingga hanya menghasilkan konflik. Sebagai contoh adalah aturan teknis mengenai Musyawarah Desa (Musdes) dalam Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Regulasi ini sangat teknis dan detail, termasuk tempat duduk, sehingga dapat berimplikasi pada terbatasnya partisipasi warga dalam Musdes. Padahal, semestinya bukan tentang prosedur, melainkan substansi demokrasinya.Yakni, masyarakat bisa duduk memahami masalahnya, mencari jalan keluar, mencoba menyelesaikan dengan melibatkan seluruh kekuatan di dalam masyarakat dan ada kapasitas belajar bersama-sama secara terus menerus.
Hasil studi penulis yang tertuang dalam disertasi Konstruksi Pemaknaan Ritual Kematian sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Kebajikan Sosial dalam Perspektif Bergerian tentang bagaimana masyarakat melakukan transformasi menafsir ulang tentang ritual kematian menjadi pemahaman baru, melembagakannya dalam bentuk rukun kematian dan lahirnya kemanfaatan sosial di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Ada contoh kebajikan sosial (social virtue) dengan munculnya “gerakan moral” untuk merespon terjadinya kemerosotan nilai kolektif (seperti dilansir oleh Fukuyama). Dengan nilai kebajikan sosial ini, degradasi dan “defisit makna” dapat tersembuhkan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Pajeng pada awal tahun 1990. Beberapa orang tersentak pilu saat terjadi peristiwa Ibu R dipanggil sowan ing ngarsaning Pangeran (dipanggil menghadap kehadirat-Nya). Hanya sedikit warga yang ber-takziah. Ditambah lagi, Ibu R yang miskin, kini harus melimpahkan bebannya kepada keluarganya. Yakni, “kewajiban sosial” untuk memenuhi serangkaian ritual kematian yang berat bagi mereka. Mereka yang tersentak itu mempertanyakan dan menafsir ulang atas ritual kematian yang mapan dan mengakar di Desa Pajeng. Melalui berbagai perbincangan, disimpulkan: ritual ini adalah aktivitas memiskinkan dan tidak produktif, yang miskin malah akan semakin miskin.
Berdasarkan fakta itulah, mereka menggagas pembentukan Rukun Kematian (RK). Dua tujuan dari pembentukan RK ini, pertama, memperbaharui praktik (redesain) ritual kematian memastikan agar warga yang miskin tidak semakin miskin; kedua, memastikan RK memiliki manfaat (utility) bagi kepentingan bersama. Suatu spirit yang dilandasi oleh prinsip untuk mengusahakan manfaat atau akibat baik yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang di dalam tindakan-tindakannya.
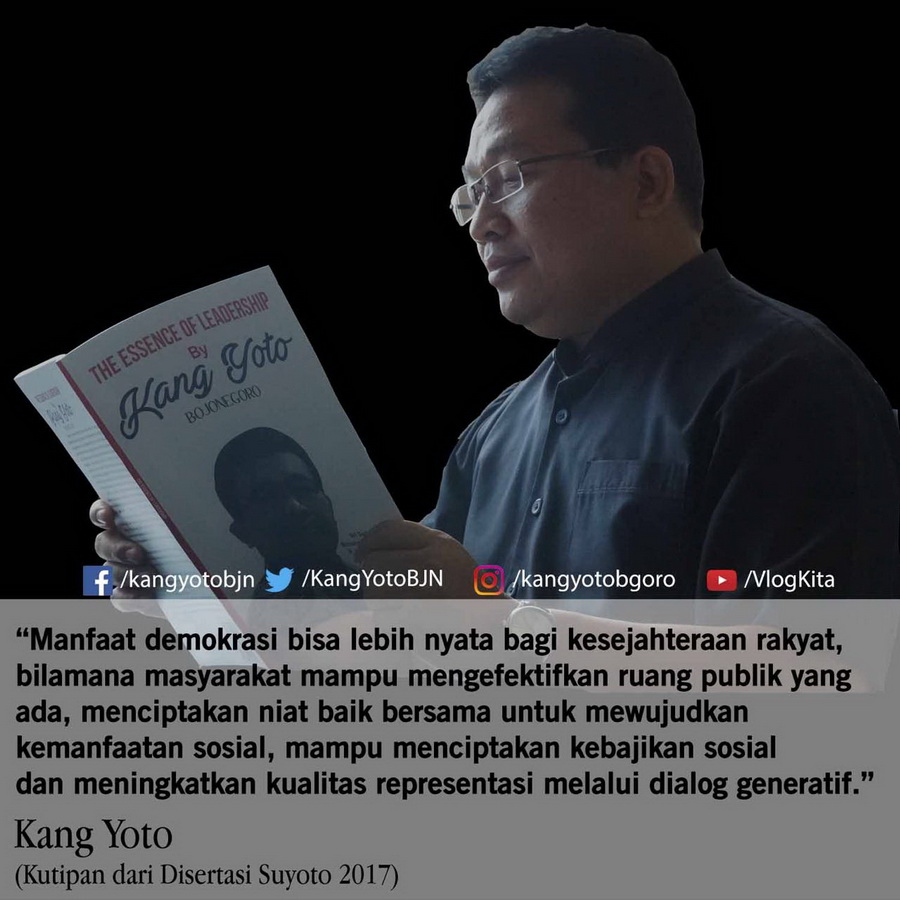
Prinsip kemanfaatan dan keadilan ini terus disosialisasikan para penggagas RK dari sejak mengawali pendirian RK sampai dengan saat ini dalam rentang 20 tahunan. Berbeda dengan pelibatan rasionalitas dalam memenuhi utilitas, namun dilandasi oleh spirit “Ngregani, bantu lan peduli liyan” (menghargai, membantu dan kepedulian pada pihak lain). Spirit liyan ini merupakan kekhasan dari prinsip keselarasan, kerukunan dan harmoni dalam etika Jawa. Maka proses pelembagaan nilai-nilai kebajikan sosial RK pun tidak bersifat instan dan seragam. Dalam spirit “kemanfaatan sosial” yang dimanifestasikan pada upaya ngregani, bantu lan peduli liyan inilah, pada akhirnya terjadi proses diskursif dalam ruang-ruang publik di Desa Pajeng. Bahkan, dari rukun kematian akhirnya muncul gerakan lain untuk pembangunan masyarakat, seperti kewirausahaan dan mengusahakan saluran air minum.
Studi dari Desa Pajeng itu menggambarkan bahwa demokrasi (baca: self governance) bisa membawa kemanfaatan bagi kesejahteraan secara nyata, bilamana 5 (lima) hal berikut terpenuhi, yaitu: Pertama, masyarakat mampu mengefektifkan ruang publik. Kedua, adanya niat bersama untuk mewujudkan kemanfaatan sosial. Ketiga, terciptanya kebajikan sosial. Keempat, meningkatnya tingkat kualitas representasi. Dan, kelima, terwujudnya dialog generatif.

Dialog generatif (generative dialogue) adalah istilah yang diciptakan oleh Otto Scharmer yang mengacu pada penangguhan prasangka untuk membiarkan pemikiran dan gagasan baru menjadi tercipta selama proses dialog. Dialog generatif terjadi pada saat komunitas bekerja bersama menghadapi tantangan tertentu terlibat dalam dialog, mereka akan memiliki visi bersama, menentukan nilai yang akan memandu tingkah laku dalam budaya komunitas, dan menciptakan misi dan tujuan yang jelas.
Praktik ini disebut dialog generatif karena komunitas tersebut memiliki visi dan komitmen untuk masa depan. Demi menghasilkan kerangka berpikir, makna bersama, dan pandangan dunia kolektif. Dalam penelitian ini, dialog generative digambarkan ketika setiap orang dalam komunitas atau masyarakat bersedia melupakan masa lalu, melihat masa depan yang lebih baik, lalu berkumpul bersama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dari sini muncul ruang publik, niat bersama, kebajikan sosial, tingkat representasi yang pada akhirnya melahirkan konsensus-konsensus sosial baru.
Secara empirik, terjadinya dialog generatif diawali dari tahap pertama yang dalam bahasa Jawa disebut “antem-anteman” atau debat kusir atas suatu persoalan/issue yang tengah di hadapi. Dari antem-anteman berkembang menjadi saling sindir, ngeles, “gedabrus”. Semua yang berdebat saling mengeluarkan dasar pemikirannya, ada yang memedomani kitab sucinya, keyakinan leluhur atau norma-norma lain sesuai yang diyakininya. Ketiga, dari gedabrus dan adu konsep dasar, masing-masing pihak mulai bisa berusaha mendengar pihak lain, maka yang terjadi adalah forum kongkow, cangkrukan, dan jagongan secara informal misalnya di warung-warung kopi. Tahap berikutnya terjadilah rembugan, masing-masing pihak yang telah berusaha saling memahami dan mengerti bisa memadukan hasil pemikirannya menjadi sebuah konsensus baru dalam forum rembugan atau musyawarah. Musyawarah inilah yang merupakan dasar dari demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan di Jawa.
Dari studi ini, penulis menemukan formula yang dinamakan Generative Self Governance (GSG), yang merupakan hasil interpolasi dari Ruang Publik (RP), Nila-Nilai Kebajikan Sosial (NKS), Kualitas Representasi (KR), intensi bersama untuk Kemanfaatan Sosial Ekonomi (KSE) dalam Dialog Generative (DG). Secara matematis formulanya: GSG=(RP+NKS+KR+KSE)DG
Model matematika ini dapat digunakan untuk melengkapi keterbatasan dari perspektif kontruksi sosial yang belum memiliki kerangka metodologi serta perspektif tindakan komunikatif yang hanya fokus pada rasionalitas dan kompetensi komunikatif. Pada tataran praktis, formulasi model analisis tersebut dapat dimanfaatkan untuk memotret indeks tentang generative self governance masyarakat pedesaan di Jawa, sehingga akan memberi arah yang jelas tentang bagaimana mereka mengembangkan dirinya dan mengidentifikasi jenis intervensi yang relevan.(*/imm)
*) Penulis adalah Bupati Bojonegoro
Tulisan ini ringkasan disertasi doktoral penulis yang dipertahankan di Universitas Muhammadiyah Malang, pada Sabtu (23/09/2017)
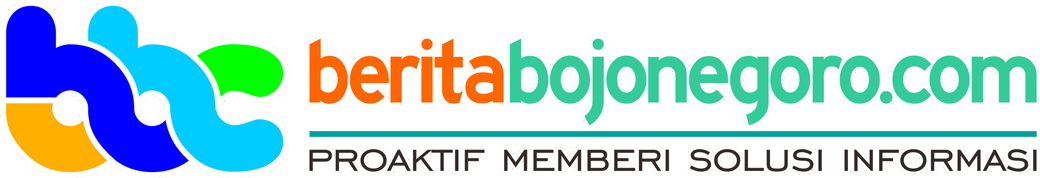


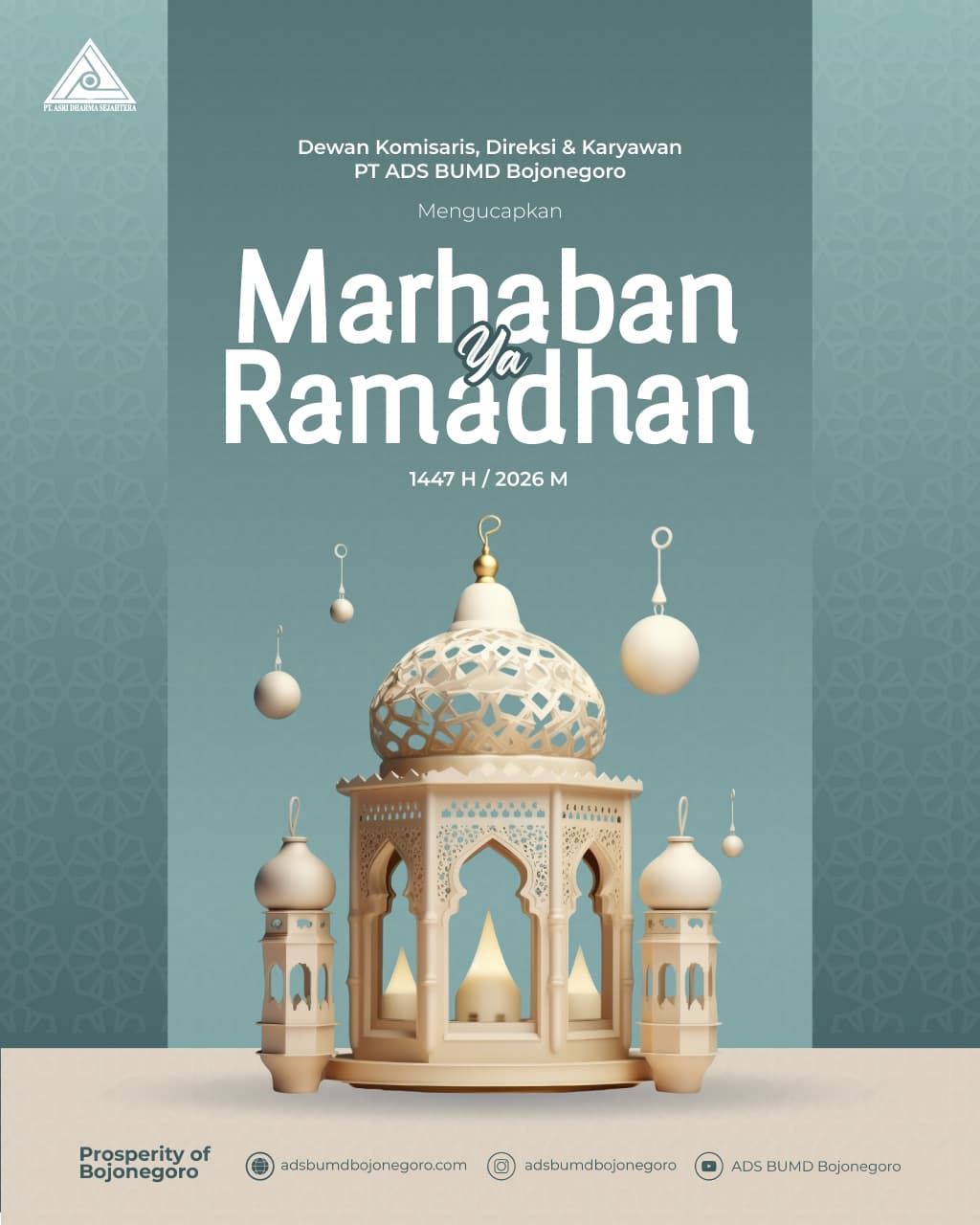





















.sm.jpg)







.md.jpg)






