The Fang of the Fire Tiger, Karya Mala Khamchan
Tentang Bagaimana Binatang Mengajari Manusia Hidup
Jumat, 06 November 2015 09:00 WIBOleh Ashri Kacung
Oleh Ashri Kacung
[Identitas Buku : Judul The Fang of the Fire Tiger Penulis Mala Khamchan Penerjemah Patsita Charoenrakhiran; Pattiya Jimreivat Editor Peter Hall Penerbit Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, 2011 Halaman 184 Bahasa Inggris]
ADA beberapa kemungkinan yang Anda dapatkan ketika selesai membaca sebuah novel. Selain bisa mengambil sudut yang paling disukai, Anda juga bisa melupakan mana yang sekiranya Anda benci. Artinya, Anda bisa mencuplik tema yang sesuai dan Anda inginkan untuk dilihat dengan seksama, sebagaimana Anda melakukan zoom in pada gambar yang Anda ingin lihat secara detail. Namun Anda juga bisa mengabaikan hal-hal yang tidak membuat hati tergerak. Betapapun, tentu saja cerita yang baik akan memiliki banyak sisi menarik yang bisa Anda perbesar/zoom in dengan segala lapisan pemahaman, pemikiran, yang membalut Anda sebelumnya.
Bukankah hampir selalu ada alasan subjektif untuk selalu memilih cerita apa yang akan kita baca? Saya katakan hampir selalu karena manusia ujung-ujungnya selalu berurusan dengan diri sendiri, tanpa menafikan bahwa ia juga makhluk sosial. Seperti ketika saya memilih untuk membaca dan menyelesaikan novel karya penulis Thailand ini.
Sampai detik ini, saya hanya memiliki empat novel penulis Thailand dalam bahasa Inggris, karena belum memungkinkan membaca dalam bahasa Thai. Ini adalah novel ke empat yang saya dapatkan, namun jadi kedua yang bisa saya selesaikan. Pertama sudah saya ulas sebelumnya, yakni The Moonlit Shore karangan Prachakom Luncahai tentang seluk beluk kemiskinan nelayan.
Kenapa saya bisa menyelesaikan buku ini, tak lain karena bagi saya ceritanya menarik. Yakni tentang pergulatan dan pergumulan hidup keluarga miskin di daerah Thailand utara, tepatnya di Desa Hui Sang Kham, Provinsi Chiang Mai, yang berbatasan dengan Burma. Entah kenapa saya selalu tertarik untuk mencari tahu tentang cerita-cerita yang miris dari orang-orang yang tersisih, miskin, gelap, hidup di desa dengan segala problematika yang mereka hadapi. Atau memang kemiskinan masih merupakan isu yang seksi –minimal menurut saya- untuk terus menerus diceritakan? Alasan berikutnya tak lain mungkin karena saya sedang melakukan studi di negeri gajah putih ini, maka membuat saya merasa tertarik untuk melihat lebih jauh kebudayaan masyarakatnya melalui sastra.
Novel ini bercerita tentang satu keluarga miskin di desa Hui Sang Kham, dekat hutan di wilayah perbatasan Chiang Mai dan Burma. Anak perempuan keluarga itu begitu bangga menemukan taring macan api. Taring yang dipercaya oleh seluruh penduduk bisa menangkal bahaya apapun. Orang yang memiliki taring itu dianggap bisa melawan siapapun dan tak terkalahkan. Kalau ia seorang pemburu, maka ia akan jadi pemburu yang hebat tak tertandingi.
Taring api itu ia temukan ketika dua bersaudara sedang memburu Thang, seekor macan tua yang akhir-akhir itu meresahkan penduduk desa karena sering mencuri hewan peliharaan mereka. Anak perempuan itu ikut serta.
Suatu sore, ketika hutan mulai gelap dan hujan akan turun, dua orang saudara dan anak perempuan itu berlindung di sebuah goa. Tak dinyana, ketika sampai pada mulut goa, si anak perempuan merasa aneh karena di sana terdapat tulang macan api. Dua bersaudara itu mendekati goa. Mereka merapal mantra dan doa penghormatan pada sang macan api. Tiba tiba goa longsor dan menghantam tubuh mereka. Salah satu orang tak bisa bertahan dan terpelanting hingga membuat tulang kakinya retak dan sulit berjalan.
Selepas longsor usai, anak perempuan itu kembali ke dekat gua dan menemukan gigi taring sang macan api, benda yang sangat jarang bisa ditemukan bahkan dalam kurun waktu 100 atau 1000 tahun sekalipun. Benda yang begitu keramat bagi orang-orang yang hidup di sekitar hutan.
Nama anak perempuan itu Kaewhuean. Usianya baru 13 tahun ketika menemukan taring sang macan api itu. Dua bersaudara adalah ayahnya, Thunna, dan sang paman, Mangkhala.
Dalam bacaan saya, novel ini melukiskan kecemasan seorang ibu menghadapi problematika keluarganya dengan balutan kemiskinan di suatu daerah tepi hutan perbatasan Thailand Utara dengan Burma.
Kecemasan pertama datang dari anak perempuannya, Keawhuean, yang ikut ayah dan pamannya berburu ke hutan lalu menemukan gigi taring itu. Yang Keawhuen dapati bukanlah sembarang taring, melainkan taring seekor macan api, hewan penguasa rimba raya, makhluk yang paling ditakuti oleh semua hewan, bahkan juga oleh roh-roh penguasa hutan. Karenanya, taring itu menjadi sangat istimewa hingga layaknya jimat. Ia dipercaya bisa menaklukan segala jenis serangan hewan dan juga roh jahat penguasa hutan. Semua penduduk desa mafhum bahwa taring itu sangat berharga dan teramat sulit mendapatkannya meskipun dalam kurun waktu seratus atau seribu tahun sekalipun. Dianugerahi penemuan taring, si anak perempuan menjadi begitu pemberani dan menetapkan cita-citanya sebagai pemburu, sebagaimana sang ayah dan kakeknya, juga buyut dan pendahulu-pendahulunya.
Namun Keawhuen adalah perempuan, yang tentu bertentangan dengan tradisi masyarakat hutan, bahwa pemburu hanyalah lelaki. Jikapun ada pemburu perempuan, maka nasibnya tak akan lebih baik, sebagaimana akhir riwayat Sangkhaem, pemburu perempuan yang mati diterkam harimau. “the fang may be good thing, but your father’s leg is better. If i could, i would trade it with your father’s leg. With the leg you can plow a paddy field and hunt in the forest. The fang might be precious like the great black germ of indra, but i don’t want it.” Hal. 15
(Terj:Taring itu memang barang berharga, tapi kaki ayahmu tentu lebih baik. Jika mampu, saya akan menukarnya dengan kaki ayahmu. Dengan kaki kau bisa membajak sawah dan berburu di hutan. Taring mungkin berharga seperti kuman hitam sebuah indra, tetapi saya tidak butuh itu-ed)
Kecemasan kedua adalah pada nasib Thunna, suaminya (ayah Kaewhuean). Lelaki itu diharapakan dengan tenaganya bisa bekerja di ladang dengan baik. Celakanya, Thunna, yang secara harfiah berarti manusia batu, tulang kakinya retak saat longsor goa saat perburuan itu.
Thunna bersikeras bahwa ia akan sembuh sebagaimana sediakala, dan hanya membutuhkan waktu 150 hari. Ia pernah jatuh dari gajah ketika bekerja di tengah hutan Burma yang menyebabkan tulang punggungnya patah, namun ajaibnya ia bisa sembuh. Meskipun tak bisa maksimal bekerja di lading, karena kondisi kakinya yang tak memungkinkan, ia masih bisa sedikit demi sedikit merawat peternakan babi. Juga ketika panen padi tiba, ia membantu sebisanya. Sebagai ayah, ia juga menepis kecemasan istrinya bahwa Keawhuaen akan menjadi perempuan tak tahu diri, melabrak adat masyarakat dan dungu. Ia percaya anak perempuannnya akan tumbuh sebagaimana anak perempuan lain. “since we brougt the fang into our house, all kind of misfortunes has hapenned to us. You lost your leg, the tiger sneaked into our house, Kaewhuean’s got bolder, Khamkhong fell into buffalo hole, and the spirits there possessess him and wanted to take him. It’s all because the fang.” Hal. 61
(Terj : Sejak membawa pulang taring itu, kesialan terus terjadi pada kita. Kau kehilangan kaki, macan menyelinap ke rumah kita, Kaewhuean lebih berani, Khamkhong jatuh ke dalam lubang kerbau, dan roh-roh jahat ingin membawanya. Ini semua karena taring itu-ed)
Kecemasan ketiga, ini terkait dengan hubungan keluarga ini dengan Khamlaeng, sang tuan tanah desa. Buachan teramat cemas ketika nanti keluarganya gagal panen, maka Khamlaeng akan memberikan hak garap ladang itu pada orang lain, meskipun keluarga ini harus menyetor separo hasil panen itu kepadanya. Di lain pihak, Buachan dan keluarga juga punya utang materiil ketika Khamlaeng menolong dan memberikan suntikan obat pada anaknya ketika terserang penyakit kuning. Juga ketika Buachan bermasalah saat melahirkan anak terakhir, Khamlaeng harus mengantarnya ke rumah sakit di Chiang Mai dan membayar seluruh biaya perawatan. Dengan semua keadaan itu, tentu saja Buachan teramat ketakutan. Sebagai konsekuensi, ia selalu menasehati anak lelakinya Khamkong untuk mengalah ketika menghadapi Somsak, anak lelaki Khamlaeng yang sering bikin perkara.
Ketika menyelesaikan novel ini, yang saya resapi antara lain adalah betapa orang miskin selalu kalah dan dikalahkan oleh tuan tanah. Dari tuan tanah inilah mereka menggantungkan hidup dengan menggarap lahan, sesekali meminta bantuan, dan juga hutang. Tentu saja hal sangat menakutkan bagi keluarga miskin ketika mereka berkonflik dengan sang tuan tanah, yang pada akhirnya akan berujung pada pengambilan hak garap tanah untuk diberikan kepada petani miskin lain, mengungkit-ungkit biaya yang si kaya sudah keluarkan. Begitu juga yang dirasakan oleh Buachan, ibu rumah tangga yang mengasuh tiga anak Kaewhuean, Khamkaew, Khamkhong. Sang suami, Thunna, baru saja mendapatkan musibah ketika berada di hutan, terpelesat menghindari longsor yang menyebabkan kakinya tak bisa berjalan dengan normal. Praktis keluarga ini tak bisa menggarap sawah dengan maksimal, yang tentu saja akan dianggap merugikan sang pemilik lahan. Padahal mereka juga harus menyetorkan separo hasil panen.
Namun apa yang menarik adalah ketika sang paman Mangkhala mengajari keponakan-keponakannya itu sambil berburu di hutan tentang esensi hidup seekor macan api. Mangkhala bercerita, “The heart of the fire tiger is a powerful heart. Fire tiger’s magical power is rigorous. It can overpower all the animals ... true fire tigers have got gentle and generous heart, so they can live happily with other animals.” Hal. 111.
(Terj: Macan api memiliki hati yang luar biasa. Kekuatan magisnya begitu tegas. Itu yang bisa menundukkan semua binatang... macan api sejati itu gentel dan murah hati, sehingga mereka dapat hidup damai bersama binatang lainnya -ed)
Sejak itulah mereka berdua merenungi kebiasaan, kecongkakan, dan kegilaan masa kanak-kanak. Mereka sadar harus memiliki hati yang baik kepada semua mahkluk jika ingin hidup tenteram dan nyaman bersama yang lain. Kaewhuean mulai menyadari ia adalah anak gadis yang mesti bisa memasak dan bersih-bersih rumah. Khamkhong mulai merasakan bahwa ia anak lelaki yang punya harga diri dan martabat dan tak bisa direndahkan oleh siapapun. Meskipun itu anak tuan tanah.
Novel ini juga mengingatkan saya tentang karya Luis Sepulveda (Penulis Chile), Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Ada tiga kemiripan cerita pada keduanya. Pertama, cerita utama mengangkat tentang kemiskinan. Kedua, sama-sama bercerita tentang alam. Khususnya hutan yang mulai berkurang jumlahnya karena dijarah oleh kerakusan manusia. Ketiga, dan ini yang paling mendebarkan, adalah ketika kedua novel ini menceritakan tokoh utamanya berhadap-hadapan dengan binatang buas dan hanya menyisakan satu kalimat; to kill or to be killed. Meskipun, pada akhirnya, manusialah yang unggul, kemenangan atas binatang buas bagi mereka harus diikuti dengan tangis, sesal, haru dan kesedihan. Karena itu adalah penghormatan yang teramat layak bagi binatang yang seharusnya tak perlu bermusuhan dengan manusia jika alam mereka terpelihara.
Penulis adalah kerani di Komunitas LESUNG (Literary of Submarging Culture). Sekarang sedang study S2 di Thailand
Ilustrasi : thompsonart.net
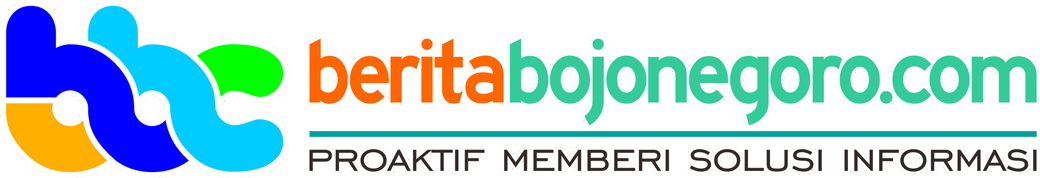
























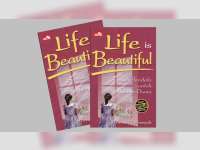






.md.jpg)






