Roman Sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman Ku Pilih Jalan Bergerilya
Sepenggal Episode Gerilya Sang Jendral
Senin, 14 Maret 2016 20:00 WIBOleh Totok AP
Oleh Totok AP
BANGSA yang hebat adalah bangsa yang bisa mengenang dan menghargai jasa pahlawannya. Inilah pesan orang bijak masa lalu, yang boleh jadi masih relevan untuk masa kini. Benarkah demikian? Ya coba rasakan sendiri dalam hati dan camkan di benak masing-masing.
Ngomong-ngomong soal pahlawan, mungkin ada jutaan pahlawan di negeri ini. Hanya segelintir yang dikenal, karena dibatasi gelar Pahlawan Nasional. Dari segelintir itu ada satu sosok pahlawan perang kemerdekaan yang sangat populer. Apalagi kalau lagi membahas seputar perang gerilya, pasti langsung terlintas satu nama itu.
Ya, siapa lagi kalau bukan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pemimpin perang kemerdekaan melawan kolonialisme Jepang dan Belanda. Sosok pahlawan bertubuh kurus dengan dandanan pakaian ala Jawa Banyumasan.
Pahlawan Indonesia satu ini mengawali pengabdian sebagai pejuang dari pasukan PETA atau Pembela Tanah Air, bentukan penjajah Jepang, memiliki sikap yang tegas. Sikap tegas dan kharismatis itu membuat dirinya kokoh dari model godaan duniawi dari para penjajah.
Sikap tegasnya kerap menempatkan Jenderal Soedirman berseberangan dengan pejuang diplomasi generasi di atasnya, seperti Sukarno, Hatta, Natsir, Wahid Hasyim dan lainnya. Ketika pejuang diplomasi lebih memilih jalan mengalah dan bekerjasama, Soedirman tetap tegas memilih melakukan perang gerilya. Sikap tegas itu ternyata sudah tertanam sejak kecil, remaja hingga dewasa.
Buku, “Ku Pilih Jalan Bergerilya”, tulisan E Rokajat Asura ini dengan segala keterbatasan berusaha mengungkap sepenggal episode jalan perang bergerilya Jenderal Soedirman. Walaupun hanya sebuah cerita roman, buku ini pantas dibaca, ditelaah, dan disarikan inspirasinya oleh generasi masa kini.
Cerita dalam roman ini diawali detik-detik pasukan baret merah Belanda menyerbu Ibu Kota RI Jogjakarta, 19 Desember 1948. Itulah yang kemudian dikenal dengan Agresi Belanda II usai perundingan Linggarjati dan Renville.
Pada hari pertama Agresi Militer II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo, dan dari sana merangsek menguasai Ibu Kota RI Yogyakarta.
Pukul 05.45 WIB lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat jenis Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7 milimeter.
Saat itu Jenderal Soedirman sedang menjalani perawatan dokter, akibat penyakit paru-paru kronis. Paru-parunya hanya bekerja sebelah saja. Kondisinya sangat lemah. Dia hanya mampu terbaring di atas tempat tidur. Batuknya kerap terdengar. Kalau sudah batuk, istrinya, Alfiah, dan ajudannya, Letnan Soeparjo Rustam, tak kuasa menahan air mata. Mereka tak tega mendengar suara batuk itu.
Kebesaran Allah berbicara. Ketika mendengar deru pesawat Mustang terbang rendah di atas genteng rumah tempatnya terbaring, Soedirman sontak terbangun. Dia lupakan sakitnya, langsung berdiri dan bergegas ke luar rumah. Dia ingin memastikan pesawat siapa yang lewat. Setelah tahu kalau itu Mustang milik Belanda, feeling pejuangnya langsung bergerak. Dia berfirasat bahwa Belanda sebentar lagi menggempur Jogja. Firasatnya terbukti. Selang satu jam, Belanda terdengar sedang memborbadir Maguwo.
Jiwa patriotismenya menggelegar. Dia lupa kalau dirinya sedang sakit keras. Rasa sakit hilang digantikan semangat membela tanah air.
Dengan tertatih, Soedirman meminta baju ganti kepada Alfiah, istrinya. Ketika ditanya hendak kemana, dia jawab akan menemui Panglima Tertinggi Bung Karno di Istana Negara. Kemauan kerasnya tak bisa dibendung lagi. Dengan ditemani Soeparjo Rustam, dia menemui Bung Karno. Saat itu kondisi Jogja sudah terjepit. Tak ada kemampuan lagi untuk melawan.
Soedirman menjelaskan keadaan darurat Jogja kepada Bung Karno. Dia memohon izin dan petunjuk untuk melawan dalam pertempuran secara gerilya. Tetapi Bung Karno menolak ikut gerilya. Sebagai pejuang dan prajurit TKR, Soedirman tetap tegas memilih melawan Belanda. Dalam buku roman ini, digambarkan sebuah percakapan menyentuh hati saat Jenderal Soedirman berdialog dengan Bung Karno.
“Sekarang yang akan memimpin perang itu, Panglima Besar atau Panglima Tertinggi?" tegas Soedirman.
Bung Karno mengernyit tapi kemudian tersenyum tenang. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dirman, kondisinya sudah begini," ucap Bung Karno.
"Siap!" Soedirman menghormat.
"Kalau Panglima Tertinggi tidak bisa memimpin, mohon izin Panglima Besar akan memimpin perang gerilya ini!” sambungnya.
“Kau masih sakit, Dirman!". Sergah Bung Karno, nada suaranya meninggi.
“Siap! Yang sakit itu Soedirman, Panglima Besar tidak pernah sakit," tandas Dirman.
Dialog tersebut adalah pembuka dari buku roman ini yang begitu hidup, mengalir deras dan membakar emosi pembaca tentang sosok sederhana namun gigih memperjuangkan rasa cinta tanah airnya. Dalam sosok Jenderal Besar ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang hidup, kegigihan, dan kecerdasan.
Bagaimana mungkin dalam kondisi sakit keras, badan lemah, jalan tertatih, dan ditandu, memendam semangat perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Hanya demi tanah air tercinta. Hidup matinya hanya untuk Indonesia. Apakah sikap cinta tanah air seperti ini juga tertanam pada generasi masa kini? Anda cari sendiri jawabnya.
Ada kisah menarik lain, ketika sudirman masih muda berusia 20 tahunan yang mulai mengenal asmara. Suatu ketika di tahun 1934, Soedirman yang saat itu tergabung dan memimpin kepanduan Hizbul Wathan Muhammaddiyah cabang Cilacap mengikuti diklat di kaki Gunung Slamet.
Udara dingin Gunung Slamet menjadi saksi kegigihan seorang Soedirman yang mampu bertahan, sementara kawan-kawan yang lain turun dan tak kuat menahan dingin puncak Gunung Slamet. Hingga azan Subuh berkumandang Soedirman tetap mampu mengalahkan rasa dingin itu.
Rupanya Soedirman memegang kata-kata Raden Suwarjo Tirtosupono, gurunya. "Susah dan senang menghadapi tantangan alam, berasal dari pikiran kowe sendiri," ujar Raden Suwarjo suata waktu. Kegigihan yang luar biasa itu akhirnya membentuk seorang Soedirman mampu mengemban tugas negara. Walau ditandu, parunya hanya sebelah yang bekerja, tubuhnya ringkih, strategi dan wibawanya mampu membuat komando yang tepat dan dahsyat.
Namun, Soedirman tetaplah manusia biasa. Sang pejuang gerilya itu pun akhirnya tak mampu melawan penyakitnya. Pada 29 Januari 1950, Soedirman wafat. Dia wafat dalam usia masih muda, yakni 34 tahun. Dia lahir 24 Januari 1916. Sebelum meninggal, dalam buku ini digambarkan bahwa Soedirman sudah melihat tanda-tanda ajalnya bakal menjemput. Karena itu sebelum tutup usia, dia masih sempat memanggil Alfiah, istrinya. Dia berbicara dengan jiwa yang tenang dan penuh optimisme.
"Aku bangga sekali, Bu. Sepanjang hidupku Gusti Allah memberikan jalan yang sederhana, dekat dengan alam, anak-anak, dan rakyat yang hidup dengan pikirannya sederhana. Rasanya tugasku sudah selesai. Kalau pun pada akhirnya dipundut sing kagungan, aku rela," ujar Soedirman.
Itulah sepenggal kisah seorang pahlawan Indonesia. Meski hanya sebuah roman, kisah ini sangat patut untuk diteladani. Bukankah demikian?! (*)
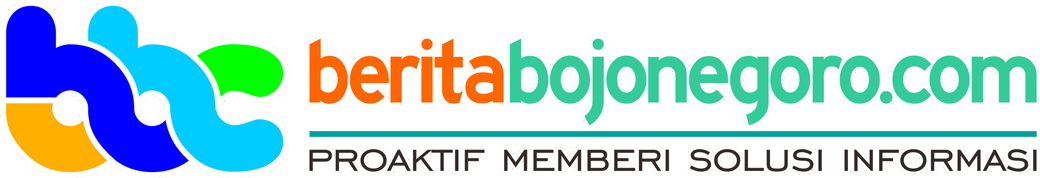

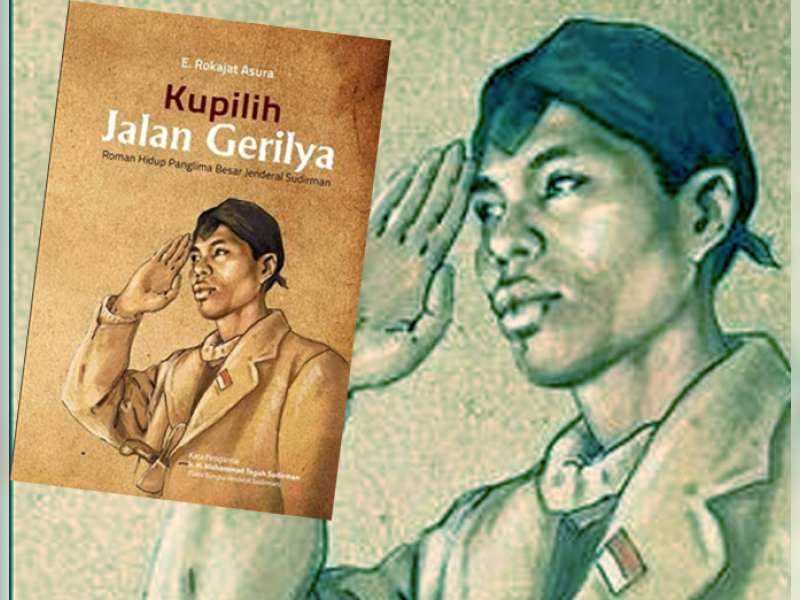























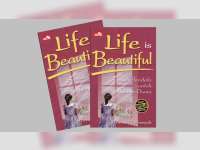





.md.jpg)






