Hikayat Pungli
Sabtu, 29 Oktober 2016 22:00 WIBOleh Totok AP
Oleh Totok AP
ISTILAH pungli alias pungutan liar kembali naik daun. Apalagi setelah Presiden Jokowi membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pada 21 Oktober lalu.
Katanya, pungli sudah membudaya di negeri ini. Maka harus disapu bersih agar investor tak takut masuk negeri ini. Rakyat jadi susah akibat pungli. Dan, bla...bla...alasan lainnya.
Sebenarnya, kenapa to pungli mesti diperangi? Dari kaca mata siapa pungli harus diperangi? Untuk kepentingan siapa? Benarkah rakyat susah karena pungli? Seberapa mudaratnya pungli sehingga harus diperangi? Apakah pungli itu memang tak ada manfaatnya?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus saja berputar-putar mengelilingi pungli. Tapi biarlah, penulis tak akan cari jawabnya. Sebab memang tak punya kuasa menjawabnya. Biarlah rumput bergoyang yang temukan jawabnya.
Penulis hanya hendak berkisah. Untuk lebih enaknya, kata “penulis” diganti “saya” aja ya.
Suatu malam, saya bersama istri jalan-jalan di Kota B. Lalu, mampir di
satu toko yang cukup laris. Usai parkir motor di bahu jalan protokol depan toko, saya dan istri masuk ke dalam toko.
Setelah membeli dan membayar barang, saya dan istri pun balik kanan. Ketika menuju motor, saya lihat ada seorang jukir alias juru parkir dengan seragam dinas lengkap. Saya pun menaiki motor. Sementara istri saya membuka dompet dan menarik keluar lembaran dua ribuan. Saya pun pun menegur, “Jangan dikasih jukir bu, itu termasuk pungli.”
Sebenarnya jukir juga tak akan kutip ongkos parkir. Karena dia paham di Kota B itu ada program parkir berlangganan. Komandannya juga sudah tegas-tegas melarang, jukir jangan sampai mengutip dan menerima ongkos parkir. Kalau sampai terima, maka akan langsung dipecat. Tapi...sssst...itu kalau tertangkap basah. Kalau tak konangan, atau tak dilaporkan ya aman-aman saja.
Kembali pada cerita. Setelah saya tegur, istri malah menjawab dengan nada enteng. "Wo alah pak, wong hanya dua ribu saja kok dianggap pungli segala..., nggak apa-apa lah etung-etung sedekah kepada jukir. Mereka kan sudah jagain motor kita. Dia juga punya keluarga, biar dipakai untuk keluarganya," ucapnya sambil ngeloyor menyerahkan uang dua ribu kepada jukir.
Si jukir mula-mula malu-malu. Tapi dia menerimanya juga sambil tersenyum dan bersemangat menyeberangkan motor saya. Dia tiup peluitnya keras-keras, sekaligus menyilakan saya melanjutkan perjalanan. Tak lupa berucap, "Terima kasih Pak."
Ada kisah satu lagi. Saat itu saya tengah mengurus surat-surat keluarga semacam KK dan KTP ke salah satu kelurahan di Kota B. Setelah menyerahkan surat pengantar dari RT dan RW kepada salah satu pegawai kelurahan, saya diminta menunggu.
Petugas itu memeriksa dan menanyakan hal-hal seperlunya. Lalu, dia berdiri dan melangkah menuju ruangan kepala kelurahan. Tiga puluh menit kemudian petugas itu keluar dan menyerahkan berkas pengantar pengurusan KK dan KTP ke kecamatan kepada saya.
Karena di depan kantor tertulis semua layanan gratis, maka saya pun langsung mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Baru saja hendak melangkah, ada seorang ibu pegawai kelurahan lain yang menegur.
Nadanya sedikit keras dan menyindir. “Pak, aja lali isi kotak-e.”
Saya paham maksudnya. “Lho mbayar to Bu?” jawab saya nggobloki. “Apa sing gratis jaman saiki, Pak,” ketus si ibu.
Dengan sedikit rikuh saya bertanya, “Berapa, Bu?” Dijawabnya,”Terserah sampeyan.”
Saya pun merogoh saku menarik uang sepuluh ribuan. Tapi saat mau memasukkan kotak yang dimaksud ibu tadi, saya tak menemukannya. “Teng pundi kotak-e, Bu?” tanya saya.
Tak disangka ibu itu langsung menjawab dengan gerakan. “Ning kene lho Pak kotak-e,” ucapnya sambil tangannya menunjuk bagian dadanya. Itu berarti uang itu minta diserahkan kepadanya. Melihat ulah ibu itu rekan pegawai kelurahan lain hanya diam dan senyum.
Maaf selingan. Ulah si ibu itu dengan menunjuk bagian dada mengingatkan penulis pada kebiasaan para bapak-bapak terhadap Ledek atau penari tayub. Dulu, mungkin sekarang tidak lagi, setiap saweran yang ditujukan padanya selalu minta diselipkan ke belahan...(maaf sensor) dadanya alias dibalik kembennya.
Tapi, apakah mungkin ibu pegawai kelurahan itu mau, kalau misalnya penulis nekat menyelipkan uang sepuluh ribu di balik baju dinasnya. Bisa-bisa penulis dihajar dan disangka pelecehan seksual he...he...he.
Kedua kisah tadi, mungkin bisa dijadikan gambaran, meski belum begitu pas, bagaimana sebenarnya situasi pungli itu. Kisah istri saya dengan jukir adalah pungli yang tak sadar. Karena pemberian ikhlas dan bentuk terima kasih pemilik motor.
Sementara bagi jukir, sebenarnya pemberian itu tetap larangan. Tapi kalau namanya dikasih “rejeki” ya rela hati diterima saja. Lumayan untuk tambahan pendapatan. “Ssssst..., tapi jangan dilaporkan ke komandan saya ya,” mungkin ini gerutu si jukir.
Lalu kisah ibu pegawai kelurahan itu, bisa termasuk pungli yang dipaksakan. Dan sudah diketahui, mungkin juga sudah disetujui dan disepakati pimpinan dan lingkungan kerjanya. Sayangnya penulis tak menelusuri, dibagi kepada siapa saja dan berapa, uang yang terkumpul “di kotak” si ibu nanti. Biarlah, lemah teles saja.
Kembali bicara pungli, memang ada dua situasi. Satu sisi diberi tanpa meminta, sisi lain meminta bahkan memaksa, kalau ndak diberi bisa-bisa malah mengancam. Lalu mana yang mesti disapu bersih? Pembacalah yang lebih tahu. (*)
*) Ilustrasi dari kompasiana.com
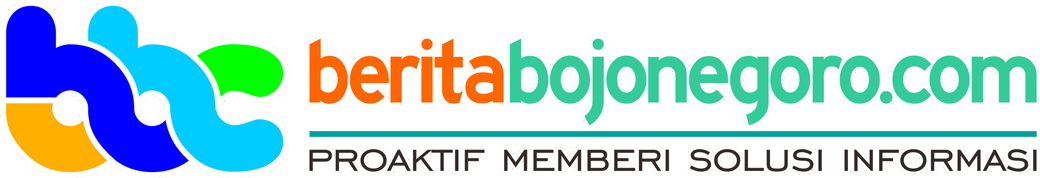































.md.jpg)






